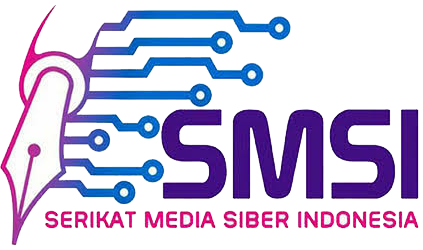Oleh: Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
KETIKA seorang pejabat publik menyampaikan pembelaan diri dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim dan disertai sumpah wallahi, billahi, tallahi, publik sesungguhnya tidak sedang membaca dokumen hukum. Publik sedang dihadapkan pada sebuah pernyataan moral yang sarat dengan dimensi iman, tetapi berada di tengah proses negara hukum yang menuntut pembuktian rasional dan terbuka.
Surat pernyataan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, yang beredar luas di ruang publik, memuat permohonan maaf sekaligus penyangkalan tegas atas tuduhan pemerasan, permintaan setoran kepada ASN, ancaman mutasi, serta penerimaan uang. Ia juga menegaskan bahwa dana yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan tabungan keluarga untuk keperluan kesehatan anaknya.
Pernyataan tersebut, secara etis, adalah hak setiap warga negara termasuk pejabat untuk membela diri. Namun, ketika pembelaan itu disampaikan dengan bertumpu pada sumpah religius, persoalan yang muncul bukan hanya soal benar atau salah, melainkan bagaimana negara hukum memposisikan moral personal dalam ruang pertanggungjawaban publik.
Dalam demokrasi konstitusional, kekuasaan tidak dinilai dari kesalehan personal, melainkan dari kepatuhan terhadap hukum dan kesediaan untuk diuji secara objektif.
Sumpah adalah wilayah keyakinan individual; pembuktian adalah wilayah institusi. Keduanya dapat berjalan seiring, tetapi tidak dapat saling menggantikan.
Di titik inilah publik kerap berada dalam dilema. Di satu sisi, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, yang menghormati sumpah atas nama Tuhan.
Di sisi lain, pengalaman panjang menghadapi kasus korupsi pejabat publik membuat masyarakat semakin berhati-hati. Bukan karena publik kehilangan kepercayaan pada agama, melainkan karena berulang kali menyaksikan bagaimana sumpah moral tidak selalu sejalan dengan fakta hukum.
Karena itu, tuntutan utama publik bukanlah sumpah tambahan, melainkan keterbukaan proses: alur peristiwa yang jelas, alat bukti yang diuji, saksi yang diperiksa, serta penegakan hukum yang berjalan tanpa prasangka dan tanpa tekanan opini. Negara hukum bekerja bukan dengan keyakinan, tetapi dengan verifikasi.
Pada saat yang sama, aparat penegak hukum juga memikul beban etis yang tidak ringan. Penetapan status hukum seseorang harus diikuti dengan proses yang cepat, cermat, dan akuntabel. Penahanan dan penyitaan bukanlah tujuan, melainkan bagian dari proses menuju kejelasan hukum. Ketidakpastian yang berlarut justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru baik bagi tersangka maupun bagi publik.
Surat Abdul Wahid, pada akhirnya, adalah ekspresi moral di tengah krisis kepercayaan terhadap kekuasaan. Ia mungkin menyentuh nurani sebagian orang, tetapi ruang penentuan kebenaran tetap berada di pengadilan dan mekanisme hukum yang sah. Justru karena sumpah itu membawa nama Tuhan, publik berhak berharap bahwa kebenaran akan diuji secara terang, jujur, dan tuntas. Di sanalah martabat kekuasaan dipertaruhkan. Dan di sanalah negara hukum menemukan maknanya, salam sehat untuk Gubri nonaktip Abdul Wahid.*