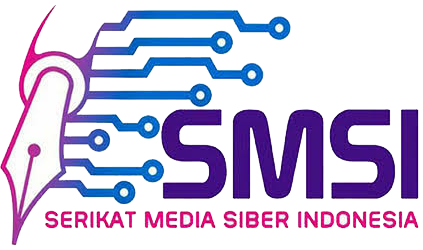Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
DI SAAT Pemerintah Provinsi Riau menghadapi defisit anggaran sebesar Rp1,2 triliun, keputusan menggelar kegiatan pemecahan Rekor MURI tari zapin kebaya labuh kekek dengan melibatkan 6.000 peserta mengundang pertanyaan publik. Bukan semata soal budaya yang ditampilkan, melainkan tentang waktu, prioritas, dan rasa kepantasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pelestarian budaya merupakan amanat konstitusional dan bagian penting dari jati diri bangsa. Zapin dan kebaya labuh adalah warisan yang patut dirawat. Namun, dalam konteks fiskal yang terbatas, setiap kebijakan anggaran semestinya diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat luas. Defisit bukan sekadar angka, melainkan cerminan ruang gerak pemerintah yang kian menyempit dalam memenuhi pelayanan dasar.
Konteks ini menjadi lebih sensitif ketika kegiatan tersebut berlangsung di tengah suasana duka 1180 orang yg meninggal akibat bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ribuan warga masih bergulat dengan kehilangan rumah, pekerjaan, dan rasa aman. Dalam situasi seperti ini, publik berharap negara termasuk pemerintah daerah menunjukkan empati dan solidaritas, bukan hanya melalui pernyataan, tetapi juga melalui pilihan kebijakan. Rekor MURI, pada dasarnya, bersifat simbolik. Ia memberi kebanggaan sesaat, tetapi tidak secara langsung menambah kapasitas fiskal daerah, mempercepat pemulihan ekonomi, atau meringankan beban korban bencana.
Karena itu, yang diuji bukan legalitas kegiatan tersebut, melainkan kebijaksanaan dalam menentukan prioritas. Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, keberhasilan tidak selalu diukur dari seberapa besar acara digelar atau seberapa banyak rekor dicatat. Keberhasilan justru tercermin dari kemampuan pemerintah membaca situasi, menahan diri, dan menempatkan empati serta kepentingan publik di atas kebutuhan pencitraan. Di tengah defisit dan duka, kepekaan sosial adalah bentuk kepemimpinan yang paling dibutuhkan.**