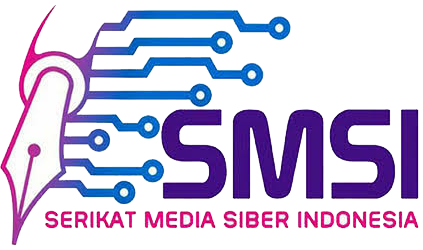Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
HAJI NO BUNKA adalah budaya malu yang menjadi fondasi kuat dalam kehidupan masyarakat Jepang. Rasa malu (haji) bukan sekadar emosi pribadi, melainkan mekanisme sosial yang mengatur perilaku, etika, dan tanggung jawab publik.
Dalam haji no bunka, kesalahan dipandang sebagai kegagalan menjaga kehormatan diri, keluarga, institusi, bahkan negara. Karena itu, pejabat yang tersandung skandal biasanya meminta maaf secara terbuka, mengundurkan diri, atau menerima sanksi moral tanpa harus dipaksa.
Tujuannya bukan pencitraan, melainkan pemulihan kepercayaan. Budaya ini menanamkan disiplin, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sejak dini di sekolah, di tempat kerja, hingga pemerintahan. Malu menjadi “pengawas” yang hidup, bekerja bahkan saat hukum belum bergerak.
Berbeda dengan masyarakat yang mengandalkan rasa takut pada hukuman, Jepang mengandalkan rasa malu untuk mencegah pelanggaran. Di situlah kekuatannya: sebelum salah dihukum, ia sudah dicegah oleh nurani.
Haji no bunka mengajarkan satu hal penting: malu bukan kelemahan, melainkan kekuatan moral sebuah bangsa.
Membandingkan rasa malu korupsi di Jepang dan Indonesia.
Di Jepang, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi aib sosial. Dalam budaya haji no bunka, rasa malu bekerja lebih cepat dari hukum. Pejabat yang terseret skandal akan meminta maaf secara terbuka, mengundurkan diri, bahkan menarik diri dari ruang publik.
Tekanan terbesar bukan dari aparat, melainkan dari nurani dan pandangan masyarakat. Keluarga, institusi, dan partai ikut menanggung rasa malu, sehingga pencegahan terjadi sejak awal.
Di Indonesia, korupsi lebih sering dipandang sebagai risiko jabatan, bukan aib moral. Rasa malu kerap tumpul. Pejabat yang diperiksa masih tampil percaya diri, membela diri di ruang publik, bahkan mengklaim dizalimi. Tekanan sosial lemah, yang kuat justru perlindungan politik dan relasi kekuasaan. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tumpuan utama, sementara pencegahan berbasis etika tertinggal.
Perbedaannya tegas, Jepang: malu mencegah, hukum menutup.
Indonesia: hukum mengejar, malu menyusul (itu pun sering tidak datang).
Pelajaran pentingnya, pemberantasan korupsi tak cukup dengan penggeledahan, pemeriksaan, OTT, vonis, dan penjara. Rasa malu harus dihidupkan kembali melalui pendidikan etika, keteladanan pemimpin, sanksi sosial yang tegas, dan transparansi publik.
Tanpa itu, korupsi akan terus berulang dengan wajah berbeda.
Jika Jepang maju karena malu, maka pertanyaannya bagi kita sederhana namun keras: masih adakah rasa malu ketika amanah rakyat dikhianati?**